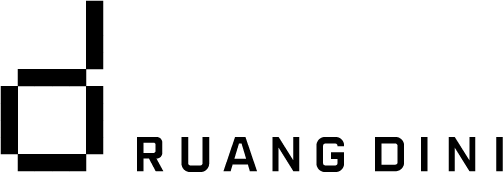Essays
Essay Titles
Content
Intentions in Manifold Dimensions
An Exhibition by Carla Agustian, Claire Sukamto, Etza Meisyara, Fika Ria Santika, Maharani Mancanagara, Nidiya Kusmaya, Rahayu Retnaningrum, Rega Ayundya Putri
1.
What is care, if we can translate it into representational artwork?
Intentions in Manifold Dimensions presents a multitude of visual interpretations of care, from material and emotional contexts. Eight artists across regionsbrought their experimentation on image-making by handling scavenged industrial waste, biotic and geotic elements, and residues of forgotten mementos. Etched mineral plates, modified plastics and films, and charcoalon surfaces that take shape as organic and geometric abstract patterns and life like depictions of objects—these artworks ocularly hinted at this question: What did we have left to lose? As care practice is for humans and the non-humans that we are connected to.
It has been a while since we survived the socially-restricted world. After beingfreed from this norm, we are now faced to reflect on what we want to do if we were not so confined. What do we care about the most? What is and was our privilege? What did we take for granted? We backpedaled aspects of our growth that we have built and seemed to have gone in the wrong pointsto zero again. We want our home, career, relationships, spirituality, health, society, institutions, and environment at large to become better. The correction becomes our drive, in the microscopic and macroscopic levels on how wegovern things in our life.
So, what is the deal with an exhibition of representational artworks, that it places importance among all of those?
In contemporary times, what is this typeof artwork’s ability compared to social art projects that directly engage andpresent within the community in responding to certain issues? One can arguethat the two-dimensional artwork in a way has the advantage to condensefragments of visually-invoking materials and stories into a tangible framework. The result is a static visual piece to be viewed with the naked eye. It can berevisited and then rekindle the optical experience for those who own it. It does have its limit to simply representing and compressing a grand scheme of things into a flat surface through visual language, not by spoken or textual diction. But the artist who devises it knows that they can deliver thoughts, not in anephemeral way like a one-time event, but rather an everlasting and observable concrete record of their gestures, crafts, and reasoning process. Care concerning the materials is shown here through the works of Maharani Mancanagara, Claire Sukamto, Nidiya Kusmaya, and Etza Meisyara in this exhibition. These artists sourced their pigments, catalysts, and surfaces fromwhat were considered remnants and have lived many lives as materials.
“Trash” is a discarded object we no longer care to find meaning and value.
Maharani revived stacks of abandoned crate woods through a fumigation process to serve as her charcoal drawings’ base. She laid her works on these woods to draw life-size utensils used in the kitchen, washroom, and bedroom (dapur, sumur, kasur) rendered in black and ochre colors. Claire saved aheap of forgotten 35 mm negative film rolls from a photo lab for her collage fragments. She formed a distorted matrix in a jesty manner of the small-sized thumbnails grid view where each image is unrecognizable from its whole picture. In Maharani and Claire’s meticulous hands, they brought our attentionto its possible reincarnated forms and ability to bridge dialogue between the past and present.
Artists took calculated and intuitive processes in handling hazardous liquid materials. Nidiya procured jelaga (carboash) from the Sukabumi power plant chimney as the coal-black pigment in her suminagshi (marbled paper) technique. Etza pilgrimed to sea in Suluban, Bali, to oxidize the salt to thecopper plate, and then etched it with liquid ammonia. Prior tothe image-making process, they ran a scientific test to gauge the safety of these chemical liquids. Once proven safe, they delicately orchestrated flowing patterns on each tabula, joining forces of these chemical slurries, the earth’s gravitation, and their hunch. It resulted in traces of ancient elemental reaction with its alluring, mysterious, and earthy characteristics yet dangerous if not controlled with care.
What is care, if we can translate it into representational artwork?
Intentions in Manifold Dimensions presents a multitude of visual interpretations of care, from material and emotional contexts. Eight artists across regionsbrought their experimentation on image-making by handling scavenged industrial waste, biotic and geotic elements, and residues of forgotten mementos. Etched mineral plates, modified plastics and films, and charcoalon surfaces that take shape as organic and geometric abstract patterns and life like depictions of objects—these artworks ocularly hinted at this question: What did we have left to lose? As care practice is for humans and the non-humans that we are connected to.
It has been a while since we survived the socially-restricted world. After beingfreed from this norm, we are now faced to reflect on what we want to do if we were not so confined. What do we care about the most? What is and was our privilege? What did we take for granted? We backpedaled aspects of our growth that we have built and seemed to have gone in the wrong pointsto zero again. We want our home, career, relationships, spirituality, health, society, institutions, and environment at large to become better. The correction becomes our drive, in the microscopic and macroscopic levels on how wegovern things in our life.
So, what is the deal with an exhibition of representational artworks, that it places importance among all of those?
In contemporary times, what is this typeof artwork’s ability compared to social art projects that directly engage andpresent within the community in responding to certain issues? One can arguethat the two-dimensional artwork in a way has the advantage to condensefragments of visually-invoking materials and stories into a tangible framework. The result is a static visual piece to be viewed with the naked eye. It can berevisited and then rekindle the optical experience for those who own it. It does have its limit to simply representing and compressing a grand scheme of things into a flat surface through visual language, not by spoken or textual diction. But the artist who devises it knows that they can deliver thoughts, not in anephemeral way like a one-time event, but rather an everlasting and observable concrete record of their gestures, crafts, and reasoning process. Care concerning the materials is shown here through the works of Maharani Mancanagara, Claire Sukamto, Nidiya Kusmaya, and Etza Meisyara in this exhibition. These artists sourced their pigments, catalysts, and surfaces fromwhat were considered remnants and have lived many lives as materials.
“Trash” is a discarded object we no longer care to find meaning and value.
Maharani revived stacks of abandoned crate woods through a fumigation process to serve as her charcoal drawings’ base. She laid her works on these woods to draw life-size utensils used in the kitchen, washroom, and bedroom (dapur, sumur, kasur) rendered in black and ochre colors. Claire saved aheap of forgotten 35 mm negative film rolls from a photo lab for her collage fragments. She formed a distorted matrix in a jesty manner of the small-sized thumbnails grid view where each image is unrecognizable from its whole picture. In Maharani and Claire’s meticulous hands, they brought our attentionto its possible reincarnated forms and ability to bridge dialogue between the past and present.
Artists took calculated and intuitive processes in handling hazardous liquid materials. Nidiya procured jelaga (carboash) from the Sukabumi power plant chimney as the coal-black pigment in her suminagshi (marbled paper) technique. Etza pilgrimed to sea in Suluban, Bali, to oxidize the salt to thecopper plate, and then etched it with liquid ammonia. Prior tothe image-making process, they ran a scientific test to gauge the safety of these chemical liquids. Once proven safe, they delicately orchestrated flowing patterns on each tabula, joining forces of these chemical slurries, the earth’s gravitation, and their hunch. It resulted in traces of ancient elemental reaction with its alluring, mysterious, and earthy characteristics yet dangerous if not controlled with care.
2.
Care is also to observe the complexity of how nature and the innerpsyche work. These reflections are present in the artworks of Rega Ayundya Putri, Fika Ria Santika, Rahayu Retnaningrum, and Carla Agustian. They zoomed in and reimagined the quotidian aspect ofthe human and non-humans through pictorial conveyance.
Rega disassembled what consisted of a self-portrait. In herdrawing, rumbling around in the backgrounds were filament-likelines and ovals inspired by microscopic photography of her bodyparts, speckled solely by pencil and charcoal on large paper.In the foreground stood the pink stripes from watercolor inks derived from menstrual cycle records in her smartphone app. Fika morphed sculptures with resin, acrylic, pigments, and lights. She germinated purported organic forms by composing sprawling thawed plastics, wires, and fluoresce hues, based on her tacit knowledge about cosmic relations. Both artists discerned organisms and lifecycles as swirly connections that intertwined with us.
Rahayu and Carla represented ways we navigate the facets of our hopes and
dreams. Rahayu juxtaposed urban and rural imagery into a surreal shangri-la visualization in her paintings. The neons of city nightlife, cats, birds, the
colossal charm of open sky, leafless trees, mountains, full moon, and geometric blocks filled the whole imaginary room. It is a cornucopia of overlooked and underlooked idyllic things that she remembered from living in the city and nowin the village. In another approach, Carla based her image on the results offolding 1000 cranes and lotus flower origami. The self-control was not onlyengaged in the meditative activity of making origamis, but also in utilizing fragile charcoal to achieve precisions in portraying realistically all the nooks and crannies of those folded papers. Their artworks are intended as spectacles to experience serenity, especially when one wonders about the choices between finding a primrose path or a silver lining in times of trepidation.
Making and observing these representational artworks is intendedas an exercise for care practices on how we see, form, and judgeperspectives in our life.
This essay is written for Galeri Ruang Dini’s Intentions in ManifoldDimensions exhibition by Gesyada Siregar
Care is also to observe the complexity of how nature and the innerpsyche work. These reflections are present in the artworks of Rega Ayundya Putri, Fika Ria Santika, Rahayu Retnaningrum, and Carla Agustian. They zoomed in and reimagined the quotidian aspect ofthe human and non-humans through pictorial conveyance.
Rega disassembled what consisted of a self-portrait. In herdrawing, rumbling around in the backgrounds were filament-likelines and ovals inspired by microscopic photography of her bodyparts, speckled solely by pencil and charcoal on large paper.In the foreground stood the pink stripes from watercolor inks derived from menstrual cycle records in her smartphone app. Fika morphed sculptures with resin, acrylic, pigments, and lights. She germinated purported organic forms by composing sprawling thawed plastics, wires, and fluoresce hues, based on her tacit knowledge about cosmic relations. Both artists discerned organisms and lifecycles as swirly connections that intertwined with us.
Rahayu and Carla represented ways we navigate the facets of our hopes and
dreams. Rahayu juxtaposed urban and rural imagery into a surreal shangri-la visualization in her paintings. The neons of city nightlife, cats, birds, the
colossal charm of open sky, leafless trees, mountains, full moon, and geometric blocks filled the whole imaginary room. It is a cornucopia of overlooked and underlooked idyllic things that she remembered from living in the city and nowin the village. In another approach, Carla based her image on the results offolding 1000 cranes and lotus flower origami. The self-control was not onlyengaged in the meditative activity of making origamis, but also in utilizing fragile charcoal to achieve precisions in portraying realistically all the nooks and crannies of those folded papers. Their artworks are intended as spectacles to experience serenity, especially when one wonders about the choices between finding a primrose path or a silver lining in times of trepidation.
Making and observing these representational artworks is intendedas an exercise for care practices on how we see, form, and judgeperspectives in our life.
This essay is written for Galeri Ruang Dini’s Intentions in ManifoldDimensions exhibition by Gesyada Siregar
Terra Nova
Exhibition by Iman Skyone & Mufti Widi
Written by Krishnamurti Suparka
1.
It was a feast for the eyes, this complication of coloured tints, a kaleidoscope of green, yellow, orange, violet, indigo, and blue; in one word, the whole palette of an enthusiastic colourist.
Jules Verne, Twenty Thousand Leagues Under the Sea
Future and past blurred; what he had already experienced and what he would eventually experience blended so that nothing remained but the moment.
Philip K. Dick, Do Androids Dream of Electric Sheep?
Terra Nova is a collaborative project between German-based artist Iman Skyone and Bandung resident Mufti Widi. It is an artistic rendering of a 3-month process of filtering and canalizing Skyone's experience in the terra nova, the new land, that is Indonesia. Through a combination of painting and new media, Skyone articulates his continued fascination with the land's colours of nature and the way local inhabitants maintain their belongings in this "culture-regulated society". A tendency to leave things in clutter and disarray, suggesting non-use and garbage; which to his German eyes is highly anomalous, if not foreign, but significantly inspiring at the same time.
The works featured in this exhibition extends Skyone's practice of juxtaposing analogue and digital elements. In a development that seeks to integrate his graffiti and street-based aesthetic with contemporary abstract shapes, colours, and supergraphics, Terra Nova also sees the intermingling of values in the form of fragmented batik patterns and Mufti Widi's digital projection mappings. A centrepiece work bearing the show's namesake is a manifestation of this transcultural union. A beamer projection on the painted work blends different materialities in an exploration of visual stimulation. One that mimics how we perceive, interpret, and respond those that arrive onto our senses and how they give shape to our reality. Skyone's virginal encounter to this land is materialised in flakes and slivers, as a reflection of the cacophonic nature of it: whether literal or metaphorical, physical or mental, internal or external. Almost an echo to the original Cubists in their attempt to establish a new vocabulary to define the reality of their time. One consisting of pieces and fragments — a collagist reality.
It was a feast for the eyes, this complication of coloured tints, a kaleidoscope of green, yellow, orange, violet, indigo, and blue; in one word, the whole palette of an enthusiastic colourist.
Jules Verne, Twenty Thousand Leagues Under the Sea
Future and past blurred; what he had already experienced and what he would eventually experience blended so that nothing remained but the moment.
Philip K. Dick, Do Androids Dream of Electric Sheep?
Terra Nova is a collaborative project between German-based artist Iman Skyone and Bandung resident Mufti Widi. It is an artistic rendering of a 3-month process of filtering and canalizing Skyone's experience in the terra nova, the new land, that is Indonesia. Through a combination of painting and new media, Skyone articulates his continued fascination with the land's colours of nature and the way local inhabitants maintain their belongings in this "culture-regulated society". A tendency to leave things in clutter and disarray, suggesting non-use and garbage; which to his German eyes is highly anomalous, if not foreign, but significantly inspiring at the same time.
The works featured in this exhibition extends Skyone's practice of juxtaposing analogue and digital elements. In a development that seeks to integrate his graffiti and street-based aesthetic with contemporary abstract shapes, colours, and supergraphics, Terra Nova also sees the intermingling of values in the form of fragmented batik patterns and Mufti Widi's digital projection mappings. A centrepiece work bearing the show's namesake is a manifestation of this transcultural union. A beamer projection on the painted work blends different materialities in an exploration of visual stimulation. One that mimics how we perceive, interpret, and respond those that arrive onto our senses and how they give shape to our reality. Skyone's virginal encounter to this land is materialised in flakes and slivers, as a reflection of the cacophonic nature of it: whether literal or metaphorical, physical or mental, internal or external. Almost an echo to the original Cubists in their attempt to establish a new vocabulary to define the reality of their time. One consisting of pieces and fragments — a collagist reality.
2.
The underlying sentiment that Terra Nova proposes is one of congruence, however contradictory it may seem in appearance. Yet this is the strength of the hypothesis. That true harmony can and does exist in difference, regardless of varieties in form and facade. Widi's role aptly serenades Skyone's conundrum through his projected digital renderings and audio components, reinforcing the multisensorial nature of the collaborative piece that is deemed necessary by the two artists. It makes a fascinating progress, this unified effort, that sees two artists from different cultural backgrounds adopting the roots of one another. A fertile source for further examination. Skyone with the materiality and traditional referents of the host culture, Widi with the technological means whose births are commonly associated with the visitor's culture. A reversal of roles that, in light of the current predilection with decolonization and emancipatory measures, serve to indicate what glimmers ahead. Of new sensibilities, new forms of care and conduct, new rules in a new land.
Krishnamurti Suparka, 3 February 2023
The underlying sentiment that Terra Nova proposes is one of congruence, however contradictory it may seem in appearance. Yet this is the strength of the hypothesis. That true harmony can and does exist in difference, regardless of varieties in form and facade. Widi's role aptly serenades Skyone's conundrum through his projected digital renderings and audio components, reinforcing the multisensorial nature of the collaborative piece that is deemed necessary by the two artists. It makes a fascinating progress, this unified effort, that sees two artists from different cultural backgrounds adopting the roots of one another. A fertile source for further examination. Skyone with the materiality and traditional referents of the host culture, Widi with the technological means whose births are commonly associated with the visitor's culture. A reversal of roles that, in light of the current predilection with decolonization and emancipatory measures, serve to indicate what glimmers ahead. Of new sensibilities, new forms of care and conduct, new rules in a new land.
Krishnamurti Suparka, 3 February 2023
1.
Menjadi seniman, bagi sebagian besar individu, merupakan perjalanan untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan eksistensialis yang hakiki. Di tengah ragam kompleksitas hidup dan pilihan profesi, menjadi seniman selalu menjadi pilihan yang tidak mudah dan tidak aman. Dalam konteks dunia yang bertumbuh dengan percepatan kapitalisme dan tawaran atas realitas-realitas baru yang dibentuk oleh teknologi, memasuki dan menghidupi seni pada dasarnya menjadi sebuah upaya untuk melihat aspek pemikiran dan penghayatan atas hidup. Seni, terutama dalam situasi negara seperti Indonesia yang infrastruktur seninya baru bertumbuh, menjadi sebuah anomali dalam dunia yang bergerak cepat dan terlipat. Seni menjadi ruang yang tersembunyi untuk merayakan kelambatan dan keterpatahan.
Karya-karya Carla Agustian berangkat dari refleksinya tentang pengalaman hidup menghadapi dunia yang kompleks dan perubahan yang tidak terbendung. Manusia bergelut dengan pengetahuan dan sensibilitas emosi yang dimiliki untuk bisa menaklukan tantangan dan persoalan kehidupan, yang acapkali hadir tak bisa diprediksi. Sebagai perempuan, pilihan dan tantangan hidup ini bisa lebih kompleks karena konstruksi sosial yang telah sekian lama menempatkan perempuan dalam ruang yang subordinat. Meskipun tidak secara langsung Carla membahas bagaimana posisi perempuan dalam ruang sosial dan personal di titik peradaban masa kini, akan tetapi tentu perspektif dan pengalaman hidupnya sebagai perempuan memberikan pengaruh besar dalam cara pandang dunianya.
Bagi Carla, refleksi hidup merupakan bentuk subjektivitas dan pandangan personal seseorang yang unik dan khas. Para seniman sesungguhnya merupakan individu yang punya keberanian untuk membagikan narasi-narasi personal ini ke dalam ruang sosial, menjadikannya sebagai percakapan bersama. Bagi Carla, titik penting dalam refleksi hidupnya adalah “penerimaan” (acceptance), yang dalam filosofi timur sering dilihat sebagai kepasrahan. Namun, Carla sendiri tampaknya melihat bahwa penerimaan adalah titik di mana seseorang (dirinya) dapat menavigasi posisinya dan melihat bagaimana ia melangkah dalam peta yang tergambar tersebut, dengan kesadaran atas risiko dan kemungkinan. Penerimaan menjadi perspektif yang mendasari Carla untuk mempersepsikan realitas dalam hidupnya, dan ini yang kemudian menjadi pijakan bagi narasi visual dalam karya-karyanya.
Metafor-metafor visual dalam karya Carla Agustian adalah citra tentang dunia yang penuh ambiguitas antara hitam dan putih, masa lalu dan masa kini, kenangan dan harapan, yang gelap dan terang, yang tampak dan tersembunyi. Dengan memilih warna-warna akromatif, cenderung monokrom, Carla menunjukkan garis-garis batas yang tegas antara ruang yang kosong dan ruang terisi, sekaligus menunjuk garis batas sebagai ruang ambang dimana kenyataan dan kemungkinan ketiga bisa ditemukan. Kanvas-kanvas Carla cenderung terisi oleh satu objek sentral, membiarkannya menjadi pusat pandangan kita, dikelilingi warna gelap yang terkadang sedemikian pekat. Di satu sisi kegelapan itu membuat objek-objek menjadi semakin menonjol, seperti dipanggungkan, membuat objek berada dalam agensi bagi narasi tertentu. Di sisi yang lain, ruang-ruang gelap juga berbicara tentang narasi-narasi lain yang tersembunyi, yang tidak tergambar dalam kisah utama.
Beberapa lukisan Carla Agustian menggunakan metafor kain putih, sesuatu yang acap muncul dalam bahasa visual praktik seni kontemporer, seperti yang kita temukan pada karya Christo dan Jeanne-Claude—tentu dalam skala yang tidak dapat diperbandingkan. Kain-kain penutup Carla bersifat intim dan rapuh, lentur tetapi seperti punya kekuatan, dan memberikan gejala aksi performatif tentang apa yang seharusnya tampak dan apa yang tidak.
Karya Amateur (2022), menampilkan lukisan “Monalisa” yang tertutup kain putih sebagian, tetapi segera membawa kita pada asosiasi bahwa lukisan itu adalah Monalisa karya Da Vinci, sebuah lukisan paling ikonik di dunia. Dengan memilih Monalisa, Carla menampilkan pandangannya tentang kanon seni, seperti gambaran tentang titik terjauh yang tak mungkin dijangkaunya. Sesuatu yang terasa dekat karena begitu sering disebut tetapi juga terasa asing dan jauh. Carla kemudian menutup sebagian lukisan dengan kain putih, seperti tidak menjadikan lukisan ini sebagai ukuran “pencapaian”, yang barangkali sering disebutkan dalam sejarah seni. Tindakan menutup kain ini seperti membangun jarak dengan imaji Monalisa, untuk meredupkan aura mistisnya sehingga kita bisa menyikapi lukisan sebagaimana adanya. Melukiskan ulang Monalisa seperti menjadi cara bagi Carla untuk meneguhkan pilihannya dalam jalan seni, tetapi juga menutupnya bisa ditafsir sebagai upaya untuk pengingat bahwa setiap seniman mempunyai cara dan jalannya masing-masing.
Menjadi seniman, bagi sebagian besar individu, merupakan perjalanan untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan eksistensialis yang hakiki. Di tengah ragam kompleksitas hidup dan pilihan profesi, menjadi seniman selalu menjadi pilihan yang tidak mudah dan tidak aman. Dalam konteks dunia yang bertumbuh dengan percepatan kapitalisme dan tawaran atas realitas-realitas baru yang dibentuk oleh teknologi, memasuki dan menghidupi seni pada dasarnya menjadi sebuah upaya untuk melihat aspek pemikiran dan penghayatan atas hidup. Seni, terutama dalam situasi negara seperti Indonesia yang infrastruktur seninya baru bertumbuh, menjadi sebuah anomali dalam dunia yang bergerak cepat dan terlipat. Seni menjadi ruang yang tersembunyi untuk merayakan kelambatan dan keterpatahan.
Karya-karya Carla Agustian berangkat dari refleksinya tentang pengalaman hidup menghadapi dunia yang kompleks dan perubahan yang tidak terbendung. Manusia bergelut dengan pengetahuan dan sensibilitas emosi yang dimiliki untuk bisa menaklukan tantangan dan persoalan kehidupan, yang acapkali hadir tak bisa diprediksi. Sebagai perempuan, pilihan dan tantangan hidup ini bisa lebih kompleks karena konstruksi sosial yang telah sekian lama menempatkan perempuan dalam ruang yang subordinat. Meskipun tidak secara langsung Carla membahas bagaimana posisi perempuan dalam ruang sosial dan personal di titik peradaban masa kini, akan tetapi tentu perspektif dan pengalaman hidupnya sebagai perempuan memberikan pengaruh besar dalam cara pandang dunianya.
Bagi Carla, refleksi hidup merupakan bentuk subjektivitas dan pandangan personal seseorang yang unik dan khas. Para seniman sesungguhnya merupakan individu yang punya keberanian untuk membagikan narasi-narasi personal ini ke dalam ruang sosial, menjadikannya sebagai percakapan bersama. Bagi Carla, titik penting dalam refleksi hidupnya adalah “penerimaan” (acceptance), yang dalam filosofi timur sering dilihat sebagai kepasrahan. Namun, Carla sendiri tampaknya melihat bahwa penerimaan adalah titik di mana seseorang (dirinya) dapat menavigasi posisinya dan melihat bagaimana ia melangkah dalam peta yang tergambar tersebut, dengan kesadaran atas risiko dan kemungkinan. Penerimaan menjadi perspektif yang mendasari Carla untuk mempersepsikan realitas dalam hidupnya, dan ini yang kemudian menjadi pijakan bagi narasi visual dalam karya-karyanya.
Metafor-metafor visual dalam karya Carla Agustian adalah citra tentang dunia yang penuh ambiguitas antara hitam dan putih, masa lalu dan masa kini, kenangan dan harapan, yang gelap dan terang, yang tampak dan tersembunyi. Dengan memilih warna-warna akromatif, cenderung monokrom, Carla menunjukkan garis-garis batas yang tegas antara ruang yang kosong dan ruang terisi, sekaligus menunjuk garis batas sebagai ruang ambang dimana kenyataan dan kemungkinan ketiga bisa ditemukan. Kanvas-kanvas Carla cenderung terisi oleh satu objek sentral, membiarkannya menjadi pusat pandangan kita, dikelilingi warna gelap yang terkadang sedemikian pekat. Di satu sisi kegelapan itu membuat objek-objek menjadi semakin menonjol, seperti dipanggungkan, membuat objek berada dalam agensi bagi narasi tertentu. Di sisi yang lain, ruang-ruang gelap juga berbicara tentang narasi-narasi lain yang tersembunyi, yang tidak tergambar dalam kisah utama.
Beberapa lukisan Carla Agustian menggunakan metafor kain putih, sesuatu yang acap muncul dalam bahasa visual praktik seni kontemporer, seperti yang kita temukan pada karya Christo dan Jeanne-Claude—tentu dalam skala yang tidak dapat diperbandingkan. Kain-kain penutup Carla bersifat intim dan rapuh, lentur tetapi seperti punya kekuatan, dan memberikan gejala aksi performatif tentang apa yang seharusnya tampak dan apa yang tidak.
Karya Amateur (2022), menampilkan lukisan “Monalisa” yang tertutup kain putih sebagian, tetapi segera membawa kita pada asosiasi bahwa lukisan itu adalah Monalisa karya Da Vinci, sebuah lukisan paling ikonik di dunia. Dengan memilih Monalisa, Carla menampilkan pandangannya tentang kanon seni, seperti gambaran tentang titik terjauh yang tak mungkin dijangkaunya. Sesuatu yang terasa dekat karena begitu sering disebut tetapi juga terasa asing dan jauh. Carla kemudian menutup sebagian lukisan dengan kain putih, seperti tidak menjadikan lukisan ini sebagai ukuran “pencapaian”, yang barangkali sering disebutkan dalam sejarah seni. Tindakan menutup kain ini seperti membangun jarak dengan imaji Monalisa, untuk meredupkan aura mistisnya sehingga kita bisa menyikapi lukisan sebagaimana adanya. Melukiskan ulang Monalisa seperti menjadi cara bagi Carla untuk meneguhkan pilihannya dalam jalan seni, tetapi juga menutupnya bisa ditafsir sebagai upaya untuk pengingat bahwa setiap seniman mempunyai cara dan jalannya masing-masing.
2.
Karya lain yang menggunakan imaji kain, Kindness (2022), terdiri dari 4 lukisan yang bersambung menjadi satu, menampilkan lipatan kain putih yang ujungnya digenggam seseorang. Carla menampilkan pesan sederhana tentang bagaimana tangan menggenggam sesuatu yang dianggap berharga dalam kehidupan, yang maknanya bisa berbeda bagi satu orang dengan orang yang lainnya.
Cahaya juga menjadi metafor penting untuk melihat bagaimana bayangan dan hal-hal yang tampak sebagai ilusi muncul dalam karya-karya Carla. Melalui dua karya, Mirror (2022) dan Pursuit of Happyness (2022), Carla menampilkan objek ini seperti separuh nyata dan separuh lagi dibentuk oleh bayangan. Bayangan menjadi ruang jeda dari realitas kehidupan, di mana ia bisa berarti juga ruang kosong di mana mimpi-mimpi dibangun. Mirror dengan semburat cahaya temaram, didasari kain yang putih, seperti membangun suasana syahdu dan sunyi. Carla meletakkan cermin untuk menduplikasi bunga dan cahaya lampu, membiarkan bayangan itu mengabur kerja jarak dan distorsi citra.
Pursuit of Happyness tampaknya menjadi bentuk yang lebih dekoratif di mana Carla menampilkan ornamen kaca dalam bentuk bayangan untuk menegaskan bagaimana cahaya seringkali datang untuk memunculkan sesuatu yang kita anggap tersembunyi dan menjadikannya lebih terang. Pada bentuk-bentuk semacam ini, Carla tampaknya menguji kembali kemungkinan still-life sebagai satu gaya dalam lukisan kontemporer, sembari saya kira, tanpa ia sadari, ia juga mempertanyakan apa makna still-life dalam lanskap produksi citra visual yang sedemikian intensif sekarang ini melalui kamera pada telepon? Carla tampaknya melihat intimasi dengan perspektif dan tema sebagai hal yang membedakan antara karyanya dengan citra-citra instan yang dibuat sebagai konten media.
Bagian terakhir dari rangkaian karya untuk pameran tunggal Carla Agustian adalah seri lukisan Magic Hands (2022), yang sengaja dibuat hampir menyatu dengan gelapnya arang. Dua tangan ini saling menggenggam, saling menyentuh, tetapi juga menunjukkan sebuah upaya untuk berjarak: seperti merengkuh tetapi juga memberi ruang untuk bertumbuh. Lima gerakan jemari tangan ini menjadi metafor yang kuat untuk “penerimaan” yang menjadi titik pijak bagi penyikapan hidup sang seniman, di mana sebagai individu ia melihat bahwa simbol tangan juga menjadi gambaran bagi filsafat hidup seseorang. Kelima lukisan ini barangkali mengingatkan kita pada citraan mudra dalam ikonografi Hindu dengan beragam bentuk jemari. Bagi Carla, menggambarkan caranya untuk mengingat dan menegaskan pada dirinya pilihan hidup dalam kerja kesenian.
Perpindahan medium dari fotografi ke lukisan merupakan cara bagi Carla untuk menghayati kembali kerja tangan, melalui sentuhan arang yang tegas dan pekat, yang memberi tekstur dan kedalaman warna hitam itu sendiri. Citra fotografi yang cenderung lebih datar ditransformasi menjadi gambaran dua dimensi yang lebih hidup, sehingga ia punya kemungkinan untuk memunculkan jiwa dan emosi manusia yang lebih personal. Dengan pilihan warna-warna yang monokromatik ini, Carla juga melihat pentingnya gradasi warna sebagai aspek pembentuk ruang dalam kanvasnya.
Karya-karya Carla Agustian pada pameran ini memang sebagian besar berangkat dari renungan personalnya tentang bagaimana ia memandang dunia saat ini, baik sebagai individu maupun sebagai seniman. Citra hitam putih menjadi pilihan artistik untuk menjawab pertanyaan dan refleksinya sendiri tentang dunia yang kerap dihadapkan pada hal-hal bertentangan: gelap/terang, hitam/putih, tampak/tidak tampak, dan sebagainya. Carla membawa dirinya pada upaya untuk membuka ruang-ruang di antara yang saling berseberangan, dan menelusuri kemungkinan yang ada pada ruang batas.
Karya lain yang menggunakan imaji kain, Kindness (2022), terdiri dari 4 lukisan yang bersambung menjadi satu, menampilkan lipatan kain putih yang ujungnya digenggam seseorang. Carla menampilkan pesan sederhana tentang bagaimana tangan menggenggam sesuatu yang dianggap berharga dalam kehidupan, yang maknanya bisa berbeda bagi satu orang dengan orang yang lainnya.
Cahaya juga menjadi metafor penting untuk melihat bagaimana bayangan dan hal-hal yang tampak sebagai ilusi muncul dalam karya-karya Carla. Melalui dua karya, Mirror (2022) dan Pursuit of Happyness (2022), Carla menampilkan objek ini seperti separuh nyata dan separuh lagi dibentuk oleh bayangan. Bayangan menjadi ruang jeda dari realitas kehidupan, di mana ia bisa berarti juga ruang kosong di mana mimpi-mimpi dibangun. Mirror dengan semburat cahaya temaram, didasari kain yang putih, seperti membangun suasana syahdu dan sunyi. Carla meletakkan cermin untuk menduplikasi bunga dan cahaya lampu, membiarkan bayangan itu mengabur kerja jarak dan distorsi citra.
Pursuit of Happyness tampaknya menjadi bentuk yang lebih dekoratif di mana Carla menampilkan ornamen kaca dalam bentuk bayangan untuk menegaskan bagaimana cahaya seringkali datang untuk memunculkan sesuatu yang kita anggap tersembunyi dan menjadikannya lebih terang. Pada bentuk-bentuk semacam ini, Carla tampaknya menguji kembali kemungkinan still-life sebagai satu gaya dalam lukisan kontemporer, sembari saya kira, tanpa ia sadari, ia juga mempertanyakan apa makna still-life dalam lanskap produksi citra visual yang sedemikian intensif sekarang ini melalui kamera pada telepon? Carla tampaknya melihat intimasi dengan perspektif dan tema sebagai hal yang membedakan antara karyanya dengan citra-citra instan yang dibuat sebagai konten media.
Bagian terakhir dari rangkaian karya untuk pameran tunggal Carla Agustian adalah seri lukisan Magic Hands (2022), yang sengaja dibuat hampir menyatu dengan gelapnya arang. Dua tangan ini saling menggenggam, saling menyentuh, tetapi juga menunjukkan sebuah upaya untuk berjarak: seperti merengkuh tetapi juga memberi ruang untuk bertumbuh. Lima gerakan jemari tangan ini menjadi metafor yang kuat untuk “penerimaan” yang menjadi titik pijak bagi penyikapan hidup sang seniman, di mana sebagai individu ia melihat bahwa simbol tangan juga menjadi gambaran bagi filsafat hidup seseorang. Kelima lukisan ini barangkali mengingatkan kita pada citraan mudra dalam ikonografi Hindu dengan beragam bentuk jemari. Bagi Carla, menggambarkan caranya untuk mengingat dan menegaskan pada dirinya pilihan hidup dalam kerja kesenian.
Perpindahan medium dari fotografi ke lukisan merupakan cara bagi Carla untuk menghayati kembali kerja tangan, melalui sentuhan arang yang tegas dan pekat, yang memberi tekstur dan kedalaman warna hitam itu sendiri. Citra fotografi yang cenderung lebih datar ditransformasi menjadi gambaran dua dimensi yang lebih hidup, sehingga ia punya kemungkinan untuk memunculkan jiwa dan emosi manusia yang lebih personal. Dengan pilihan warna-warna yang monokromatik ini, Carla juga melihat pentingnya gradasi warna sebagai aspek pembentuk ruang dalam kanvasnya.
Karya-karya Carla Agustian pada pameran ini memang sebagian besar berangkat dari renungan personalnya tentang bagaimana ia memandang dunia saat ini, baik sebagai individu maupun sebagai seniman. Citra hitam putih menjadi pilihan artistik untuk menjawab pertanyaan dan refleksinya sendiri tentang dunia yang kerap dihadapkan pada hal-hal bertentangan: gelap/terang, hitam/putih, tampak/tidak tampak, dan sebagainya. Carla membawa dirinya pada upaya untuk membuka ruang-ruang di antara yang saling berseberangan, dan menelusuri kemungkinan yang ada pada ruang batas.
R.E. Hartanto seringkali mengamati pergulatan batin kelas menengah sebagai subjekkekaryaannya. Gejolak politik, ekonomi, sosial, dan budaya nasional membuat merekamenjadi kelompok massa dengan perilaku yang dinamis. Dalam karyanya, Tanto tidak melukis manusianya, melainkan suasana batinnya. Karena itulah realisme saja iaanggap tidak cukup, yang dibutuhkan ada surrealisme. Alegori digunakan untuk membangun narasi dan makna suatu objek didorong lebih jauh untuk merangsang imajinasinya.
Tanto mulai melukis lanskap antah-berantah yang digabungkan dengan figur sejak tahun 2017 sampai sekarang, seperti yang ia ciptakan dalam Seri Limbo. Dalam Limbo, ia merefleksikan ketidakpastian dan yang tak diketahui, yang berisi kesempatan dan keberlimpahan sekaligus risiko dan kekurangan yang kita hadapi sejak pandemi dimulai beberapa tahun ke belakang. Tanto menilai bahwa ketidakpastian yang dihadapi boleh jadi merupakan kondisi sementara sembari menunggu pencapaian resolusi. Baginya, kondisi pandemi sebelum adanya vaksin membuat kita semua kebingungan dan penuh ketidaktahuan. Melalui Limbo, Tanto menggambarkan lanskap alam yang asing di dunia antah berantah—sebuah dunia yang familiar, tapi tidak masuk akal seperti yang kita hadapi setelah pandemi dimulai. Keganjilan dan ketidakpastian inilah yang ingin Tanto tangkap dalam Seri Limbo ketika manusia dipaksa untuk mengaktifkan mode bertahan hidup yang terasa berkepanjangan.
Keinginan menggambarkan suasana batin dalam upaya untuk bertahan hidup membuat Tanto secara sengaja mengubah bentuk figur realisme manusia dengan figur hewan. Pemilihan hewan sebagai objek dalam karyanya ia pahami sebagai simbol dari manusia itu sendiri. Di sini, Tanto merasa bahwa pencitraan manusia sebagai homosapiens menjadi hewan adalah hal yang tepat. Baginya, untuk merepresentasikan kebertahanan hidup, hewan liar lah yang bisa menggambarkannya.
Melalui seri Limbo dapat terlihat bahwa citra dimainkan dengan menggunakan metode jukstaposisi yang secara konsisten muncul di setiap karya. Di sini, manusia seperti berada di tempat yang dianggap tidak pada yang semestinya. Ia melakukan pemindahan (displacement) terhadap figur hewan di atas objek lanskap yang bukan habitatnya, yang Tanto sebut sebagai ketidakmungkinan geografis (geographical impossibilty). Cara ini ia lakukan untuk meninggalkan efek kontras dan menyampaikan kepada penonton bahwa pada saat krisis pandemi berlangsung, realitas nampak terasa semakin terdistorsi, membuat manusia seolah-olah teralienasi dari lingkungannya sendiri.
Melihat karya seri Limbo, membuat penonton dapat menelusuri kembali akan realitas di sekitar—tentang pola perilaku kita saat dihadapi satu krisis yang disusul dengan krisis lainnya, tentang bagaimana eksistensi kita terlempar dari keasingan yang satu dan yang lainnya, tentang bagaimana manusia secara alamiah harus bertahan hidup dalam kesadaran semunya. Pada titik ini, Limbo menjadi dunia yang tidak terelakkan oleh hampir kebanyakan orang. Kejanggalan, ketidakmasukakalan, dan kondisi morbidini yang kemudian membuat apa-apa yang hidup akan berupaya untuk tetap bertahan.Hal ini menjadikan Limbo sebagai bahan renungan, pemikiran, atau bahkan refleksi diri.
1. Dalam teologi Katolik Romawi, Limbo merupakan tempat perbatasan antara surga dan nerakayang dihuni oleh jiwa-jiwa—yang meski tidak dihukum di neraka, di waktu yang sama jugakehilangan sukacita yang kekal bersama Tuhan di surga. Dalam pengertian sehari-hari, Limbomerupakan situasi sementara yang dipenuhi ketidakpastian karena menunggu resolusi tertentu.
Flower Among Debris
A Solo Exhibition by Meliantha Muliawan
Written by Alia Swastika
1.
Ingatan masa lalu membentuk diri kita dengan cara yang kadang tak bisa kita definisikan dalam Bahasa. Ingatan menjelma hantu atau masuk melalui perasaan rindu, atau bahkan trauma, lalu pelahan seperti membentuk jalan setapak menuju titik yang tak pernah kita tahu. Ingatan membantu kita mencari diri kita yang lain, atau menelusuri tempat-tempat yang lama kita tinggalkan. Kepingan-kepingan hidup yang kemudian kita susun ulang dengan bingkai baru, menyusun gambar baru yang bertemu dengan imaji kita lainnya.
Karya Muliantha Muliawan pada pameran ini merupakan serangkaian penelusurannya di masa lalu atas peristiwa yang tampaknya lewat sepintas, tetapi justru membawanya pada satu pengalaman ketubuhan atas ruang dan konstruksi berpikir. Ia sengaja menguak masa kecilnya ketika sering turut bersama sang ke proyek-proyek bangunan untuk urusan pekerjaan. Jika Sebagian keluarga menghabiskan waktu akhir pekan untuk berlibur atau mengunjungi satu tempat bersama-sama, ayahnya sering harus terus bekerja di waktu itu. Karena sekolah tak ada aktivitas, jadilah Meliantha acap diajak mengunjungi proyek bangunan, yang tentu saja saat itu tak begitu menyenangkan baginya. Apa yang menarik dari melihat bangunan-bangunan yang belum jadi, area yang tampak terbengkalai, atau puing yang berserakan di mana-mana?
Ayah Meliantha Muliawan membuka toko bangunan “Maju Lancar” di Depok pada kisaran tahun 1980an. Dari toko ini, ia kemudian juga mulai mengerjakan proyek-proyek pembangunan perumahan atau rumah toko yang mulai marak di wilayah tersebut. Periode 1980an adalah bagian dari periode keemasan pembangunan(isme) Orde Baru, dengan dibukanya lahan-lahan perumahan baru, terutama di Kawasan pinggiran kota besar, untuk menyokong kelas menengah baru yang bekerja di sektor profesional terutama dari tumbuhnya lapangan kerja di perusahaan-perusahaan trans-nasional atau perusahan manufaktur. Perumahan skala kecil, lebih privat, terpagar, menjadi impian baru bagi keluarga-keluarga kelas menengah baru yang ingin berjarak dari kehidupan perkampungan yang lebih keos dan seperti tak memberi privasi. Pada tahapan ini, bermunculan pola kerja kontraktor skala kecil yang membangun rumah dengan modal jejaring dan kerja keras, tetapi tidak membutuhkan modal uang skala besar. Ayah Meliantha, dengan didikan keluarga keturunan Tionghoa yang diarahkan untuk menjadi pedagang, memanfaatkan kesempatan ini dengan jeli. Spirit kerja keras itu juga terlihat dari kemauan untuk bekerja bahkan di akhir pekan, melibas waktu liburnya.
Menelusur sejarah keluarga dari sisi ekonomi semacam in I secara sepintas kemudian membawa Meliantha untuk membaca ingatan ini lebih dekat. Puing-puing dan rerentuhan itu kini menjelma sebagai sesuatu yang berbeda; sisa dari struktur-struktur yang dibongkar atau dihancurkan. Dengan cara pandang dewasa, dan bekerja sebagai seniman, ia melihat puing sebagai material yang punya sejarah. Meliantha kemudian mengumpulkan puing-puing bangunan untuk menjadi material utama dalam karyanya, menyusun kepingan kenangan menjadi gambar baru yang memproyeksikan cara pandang baru.
Ingatan masa lalu membentuk diri kita dengan cara yang kadang tak bisa kita definisikan dalam Bahasa. Ingatan menjelma hantu atau masuk melalui perasaan rindu, atau bahkan trauma, lalu pelahan seperti membentuk jalan setapak menuju titik yang tak pernah kita tahu. Ingatan membantu kita mencari diri kita yang lain, atau menelusuri tempat-tempat yang lama kita tinggalkan. Kepingan-kepingan hidup yang kemudian kita susun ulang dengan bingkai baru, menyusun gambar baru yang bertemu dengan imaji kita lainnya.
Karya Muliantha Muliawan pada pameran ini merupakan serangkaian penelusurannya di masa lalu atas peristiwa yang tampaknya lewat sepintas, tetapi justru membawanya pada satu pengalaman ketubuhan atas ruang dan konstruksi berpikir. Ia sengaja menguak masa kecilnya ketika sering turut bersama sang ke proyek-proyek bangunan untuk urusan pekerjaan. Jika Sebagian keluarga menghabiskan waktu akhir pekan untuk berlibur atau mengunjungi satu tempat bersama-sama, ayahnya sering harus terus bekerja di waktu itu. Karena sekolah tak ada aktivitas, jadilah Meliantha acap diajak mengunjungi proyek bangunan, yang tentu saja saat itu tak begitu menyenangkan baginya. Apa yang menarik dari melihat bangunan-bangunan yang belum jadi, area yang tampak terbengkalai, atau puing yang berserakan di mana-mana?
Ayah Meliantha Muliawan membuka toko bangunan “Maju Lancar” di Depok pada kisaran tahun 1980an. Dari toko ini, ia kemudian juga mulai mengerjakan proyek-proyek pembangunan perumahan atau rumah toko yang mulai marak di wilayah tersebut. Periode 1980an adalah bagian dari periode keemasan pembangunan(isme) Orde Baru, dengan dibukanya lahan-lahan perumahan baru, terutama di Kawasan pinggiran kota besar, untuk menyokong kelas menengah baru yang bekerja di sektor profesional terutama dari tumbuhnya lapangan kerja di perusahaan-perusahaan trans-nasional atau perusahan manufaktur. Perumahan skala kecil, lebih privat, terpagar, menjadi impian baru bagi keluarga-keluarga kelas menengah baru yang ingin berjarak dari kehidupan perkampungan yang lebih keos dan seperti tak memberi privasi. Pada tahapan ini, bermunculan pola kerja kontraktor skala kecil yang membangun rumah dengan modal jejaring dan kerja keras, tetapi tidak membutuhkan modal uang skala besar. Ayah Meliantha, dengan didikan keluarga keturunan Tionghoa yang diarahkan untuk menjadi pedagang, memanfaatkan kesempatan ini dengan jeli. Spirit kerja keras itu juga terlihat dari kemauan untuk bekerja bahkan di akhir pekan, melibas waktu liburnya.
Menelusur sejarah keluarga dari sisi ekonomi semacam in I secara sepintas kemudian membawa Meliantha untuk membaca ingatan ini lebih dekat. Puing-puing dan rerentuhan itu kini menjelma sebagai sesuatu yang berbeda; sisa dari struktur-struktur yang dibongkar atau dihancurkan. Dengan cara pandang dewasa, dan bekerja sebagai seniman, ia melihat puing sebagai material yang punya sejarah. Meliantha kemudian mengumpulkan puing-puing bangunan untuk menjadi material utama dalam karyanya, menyusun kepingan kenangan menjadi gambar baru yang memproyeksikan cara pandang baru.
2.
Meliantha membentuk puing-puing ini menjadi kelopak bunga, mewarnainya dengan warna-warna terang seperti bunga yang cemerlang di musim panas. Bagi Meliantha, gagasan atas bunga ini juga bagian dari ziarah atas pengalaman yang sama: bahwa di antara puing dan reruntuhan, bagian paling disukainya adalah berjalan di antara bunga-bunga di taman yang berada di dalam komplek perumahan yang dibangun ayahnya. Bunga-bunga ini menjadi keindahan yang memberi kontras dari hal-hal yang berserakan di Kawasan proyek perumahan, dan Meliantha merekamnya sebagai ingatan visual yang cukup detil.
Meliantha membawa strategi bunga ala estetika gambar diam (still life), dan dengan sengaja membuat strategi bidang transparan untuk menunjukkan struktur bingkai yang menopang lukisan ini. Meliantha melihat bingkai sebagai bagian dari karya seni yang menarik untuk dipandang, bukan hanya disembunyikan. Apalagi dalam konteks konseptualisasi karya ini, Meliantha melihat puing sebagai bagian dari struktur, dan bingkai lukisan pun merupakan bentuk struktur mesti yang sederhana. Struktur geometris ini menjadi bagian dari elemen visual yang membentuk karya, sebagaimana bunga-bunga. Selain ketidaklaziman menampakkan bingkai sebagai elemen visual yang sejajar dengan objek karya, Meliantha juga berhasil memberikan kontras yang menarik dari struktur bingkai yang geometris dengan detil bunga yang penuh dengan garis lengkung (kurva).
Bentuk dan komposisi bebungaan ini juga mengingatkan saya pada bentuk kerajinan kruistik yang banyak menghiasi rumah-rumah kelas menengah pada 1980an, yang Sebagian dibuat oleh para istri melalui kelompok Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Selain bentuk bunga, Ingatan tentang konstruksi perumahan yang “keras” dan sarat dengan citra maskulin atas bahan-bahan padat industri, kemudian bertemu dengan bentuk yang lebih halus dan dibuat dengan moda kriya rumahan. Meliantha tidak hanya menawarkan pertentangan bentuk antara yang keras dan yang halus, yang massif dan yang unik, tetapi juga ingatan yang berkelindan di antara yang dianggap sampah dan apa yang indah.
Melalui pemilihan material yang sangat dengan pengalaman dan ingatan tubuhnya atas sebuah proses konstruksi bangunan, serta cerapan atas keindahan bebungaan, Meliantha membawa kita menelusuri jejak yang samar dari proses pembangunan di kota pinggiran, dari ekonomi sebuah negara yang melaju dari boom minyak dunia pada 1970an dan bagaimana gaya hidup kelas menengah baru pada saat itu. Praktik artistiknya tidak saja mengartikulasikan ingatan dan mantransformasikannya menjadi bentuk yang tak terpikirkan, tetapi memberi ruang persilangan pertemuan antara maskulin dan feminin, material keras dan bentuk yang lembut, seni tinggi dan seni sehari-hari, materialitas dan dialektika objek. Meskipun secara visual tampak sederhana; rangkaian bunga-bunga tiga dimensi yang tertempel di dinding galeri, Meliantha sedang menawarkan pembacaan atas sejarah keluarganya sebagai bagian dari narasi konteks atas lanskap arsitektur dan kota, serta negosiasi yang cerdas atas kanon sejarah seni kita.
Meliantha membentuk puing-puing ini menjadi kelopak bunga, mewarnainya dengan warna-warna terang seperti bunga yang cemerlang di musim panas. Bagi Meliantha, gagasan atas bunga ini juga bagian dari ziarah atas pengalaman yang sama: bahwa di antara puing dan reruntuhan, bagian paling disukainya adalah berjalan di antara bunga-bunga di taman yang berada di dalam komplek perumahan yang dibangun ayahnya. Bunga-bunga ini menjadi keindahan yang memberi kontras dari hal-hal yang berserakan di Kawasan proyek perumahan, dan Meliantha merekamnya sebagai ingatan visual yang cukup detil.
Meliantha membawa strategi bunga ala estetika gambar diam (still life), dan dengan sengaja membuat strategi bidang transparan untuk menunjukkan struktur bingkai yang menopang lukisan ini. Meliantha melihat bingkai sebagai bagian dari karya seni yang menarik untuk dipandang, bukan hanya disembunyikan. Apalagi dalam konteks konseptualisasi karya ini, Meliantha melihat puing sebagai bagian dari struktur, dan bingkai lukisan pun merupakan bentuk struktur mesti yang sederhana. Struktur geometris ini menjadi bagian dari elemen visual yang membentuk karya, sebagaimana bunga-bunga. Selain ketidaklaziman menampakkan bingkai sebagai elemen visual yang sejajar dengan objek karya, Meliantha juga berhasil memberikan kontras yang menarik dari struktur bingkai yang geometris dengan detil bunga yang penuh dengan garis lengkung (kurva).
Bentuk dan komposisi bebungaan ini juga mengingatkan saya pada bentuk kerajinan kruistik yang banyak menghiasi rumah-rumah kelas menengah pada 1980an, yang Sebagian dibuat oleh para istri melalui kelompok Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Selain bentuk bunga, Ingatan tentang konstruksi perumahan yang “keras” dan sarat dengan citra maskulin atas bahan-bahan padat industri, kemudian bertemu dengan bentuk yang lebih halus dan dibuat dengan moda kriya rumahan. Meliantha tidak hanya menawarkan pertentangan bentuk antara yang keras dan yang halus, yang massif dan yang unik, tetapi juga ingatan yang berkelindan di antara yang dianggap sampah dan apa yang indah.
Melalui pemilihan material yang sangat dengan pengalaman dan ingatan tubuhnya atas sebuah proses konstruksi bangunan, serta cerapan atas keindahan bebungaan, Meliantha membawa kita menelusuri jejak yang samar dari proses pembangunan di kota pinggiran, dari ekonomi sebuah negara yang melaju dari boom minyak dunia pada 1970an dan bagaimana gaya hidup kelas menengah baru pada saat itu. Praktik artistiknya tidak saja mengartikulasikan ingatan dan mantransformasikannya menjadi bentuk yang tak terpikirkan, tetapi memberi ruang persilangan pertemuan antara maskulin dan feminin, material keras dan bentuk yang lembut, seni tinggi dan seni sehari-hari, materialitas dan dialektika objek. Meskipun secara visual tampak sederhana; rangkaian bunga-bunga tiga dimensi yang tertempel di dinding galeri, Meliantha sedang menawarkan pembacaan atas sejarah keluarganya sebagai bagian dari narasi konteks atas lanskap arsitektur dan kota, serta negosiasi yang cerdas atas kanon sejarah seni kita.